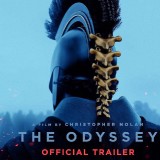TIMES SUMENEP, SUMENEP – Sekitar tahun 1880, di kota kecil Kudus, seorang lelaki bernama Haji Djamhari mencoba meracik tembakau dan cengkeh untuk meredakan sakit di dadanya. Dari eksperimen sederhana itu, lahirlah sesuatu yang kelak menjadi bagian dari jiwa bangsa: rokok kretek. Ia tak pernah bermimpi bahwa ramuan penyembuhnya akan menjadi ikon budaya Indonesia.
Nama Djamhari memang tercatat dalam sejarah, tetapi sosok yang kemudian dikenal luas sebagai Bapak Kretek Indonesia adalah Mas Nitisemito seorang wirausahawan jenius yang mengubah racikan rakyat menjadi industri nasional. Dari tangannya, aroma tembakau dan cengkeh menjelma menjadi denyut ekonomi dan simbol kebanggaan.
Namun berbicara tentang tembakau tanpa menyebut Sumenep rasanya tidak adil. Di ujung timur Pulau Madura, kabupaten ini dikenal sebagai tanah penghasil tembakau terbaik di negeri ini, bahkan kerap disejajarkan dengan tembakau srintil dari Temanggung. Tanah keringnya melahirkan daun emas beraroma tajam dan berkarakter kuat.
Di balik setiap helai daun itu ada peluh, doa, dan kesabaran petani yang menatap langit kering dengan keyakinan bahwa rezeki masih akan turun, entah lewat hujan, entah lewat daun yang dijemur di bawah matahari.
Ironisnya, di tanah yang begitu subur dengan harapan itu, para petani justru masih hidup dalam lingkar ketidakpastian. Harga tembakau yang mereka jual hanya berkisar antara seribu hingga dua ribu rupiah per pohon, atau sekitar lima puluh lima ribu hingga enam puluh ribu rupiah per kilogram.
Tak ada regulasi harga yang pasti. Petani hanya bisa pasrah pada permainan pasar, sementara pedagang dan pabrikan menikmati hasil jauh lebih besar. Seolah mereka yang menanam dan menjaga daun emas ini hanyalah figuran dalam cerita panjang industri tembakau Indonesia.
Padahal, secara historis, pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau. Di atas kertas, perda itu bertujuan melindungi petani dan menata tata niaga.
Di lapangan, aturan itu justru banyak dikritik karena lebih menguntungkan pembeli. Petani menuding adanya potongan berat tikar pembungkus, pengambilan sampel tembakau berlebih, dan kurangnya transparansi penimbangan. Akibatnya, hasil jerih payah mereka sering menyusut sebelum sampai ke tangan.
Beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep mendorong revisi perda itu. Namun pembahasan berjalan lamban. Sebagai langkah sementara, pemerintah kabupaten menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau, disusul Perbup Nomor 30 Tahun 2024.
Aturan sementara ini mencoba memperjelas mekanisme pembelian, penimbangan, dan sanksi, tetapi di lapangan tak banyak yang berubah. Para petani masih mengeluh soal harga, soal perlakuan, soal siapa sebenarnya yang berpihak pada mereka.
Sementara itu, di tingkat nasional, pemerintah telah memiliki perangkat hukum yang jauh lebih besar. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengatur produk tembakau sebagai zat adiktif.
Ia mewajibkan pengendalian iklan, promosi, dan pelabelan produk. Dasarnya ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa tembakau termasuk zat yang harus dikendalikan.
Regulasi terbaru, yakni PP Nomor 28 Tahun 2024, bahkan memperketat larangan penjualan rokok eceran, melarang penjualan kepada anak di bawah usia 21 tahun dan ibu hamil, serta membatasi penjualan di sekitar sekolah dan taman bermain.
Namun, semua regulasi itu seolah berhenti di ruang administratif. Tak ada satu pun yang menyentuh sisi paling bawah dari rantai tembakau: kehidupan petani. Negara terlalu sibuk mengatur rokok sebagai produk, tetapi lupa pada tembakau sebagai sumber hidup manusia di baliknya.
Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau WHO (FCTC), tetapi tanpa kebijakan afirmatif terhadap petani, pengendalian yang hanya bersifat moral tidak akan pernah adil.
Dalam sejarah ekonomi agraris, tembakau adalah paradoks. Ia disebut “daun emas” karena nilainya tinggi, tetapi di tangan petani, emas itu kerap berubah menjadi tembaga. Filosofi keadilan distributif menuntut agar hasil kerja dibagi secara proporsional: yang memeras tenaga semestinya mendapat bagian yang sepadan.
Ketika petani hidup dalam ketidakpastian sementara industri raksasa terus tumbuh, maka di situlah ketimpangan menjadi wajah yang telanjang. Negara tak boleh hanya hadir sebagai wasit yang diam; ia harus aktif menata ulang permainan agar semua pihak berjalan dalam keadilan yang sama.
Dalam kacamata Islam, keadilan bukan hanya konsep hukum, tetapi juga ibadah sosial. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” Hadis ini sederhana tetapi tegas: kerja manusia tidak boleh diremehkan, apalagi diabaikan.
Petani tembakau, dengan segala peluh dan ketabahannya, layak diperlakukan sebagai pewaris bumi, bukan sekadar penyedia bahan mentah industri. Jika pemerintah terus lalai, maka ketimpangan ini bukan lagi urusan ekonomi semata, tetapi pelanggaran moral dan spiritual.
Kita juga harus menengok sisi filosofis dari hubungan manusia dengan tanah. Dalam setiap ladang tembakau Sumenep, ada relasi ekologis dan kultural yang panjang. Tembakau bukan sekadar tanaman, melainkan simbol ketekunan.
Ia tumbuh di tanah gersang, menyerap garam laut, menantang matahari, dan bertahan di antara batu kapur. Ia adalah cermin dari jiwa orang Madura: keras, gigih, tak mudah menyerah. Maka memperjuangkan tembakau berarti memperjuangkan nilai hidup mereka.
Pemerintah daerah seharusnya menempatkan petani tembakau bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Revisi Perda 6/2012 tidak boleh sekadar mengganti pasal, tetapi harus merombak paradigma.
Pemerintah harus menetapkan standar harga dasar, menjamin transparansi pembelian, dan mendorong terbentuknya koperasi petani yang kuat. Kolaborasi antara pemerintah, pabrikan, dan koperasi lokal adalah kunci untuk membangun rantai nilai yang berkeadilan. Tidak ada kemajuan daerah bila petaninya terus kalah dalam permainan pasar.
Di tingkat pusat, negara perlu menyusun Undang-Undang Pertembakauan yang komprehensif. Bukan untuk menyaingi kebijakan kesehatan, melainkan untuk mengatur keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan moral.
Dengan undang-undang itu, kebutuhan industri bisa diatur tanpa mematikan kehidupan petani. Rantai produksi harus diawasi dari hulu ke hilir, dari daun yang dijemur hingga rokok yang dibakar, agar keadilan tidak berhenti di pabrik.
Sumenep, dengan segala tradisinya, bukan sekadar catatan kecil dalam peta pertembakauan Indonesia. Ia adalah laboratorium keadilan ekonomi yang menunggu keberanian moral dari para pemimpin.
Bila perda yang usang terus dipertahankan, bila petani terus dibiarkan dalam kerugian, maka aroma harum tembakau itu akan berubah menjadi asap getir yang menyesakkan nurani.
Daun emas itu kini seperti menatap kita semua: pemerintah, pengusaha, dan masyarakat seolah bertanya: apakah kalian masih peduli? Karena di setiap helaian daun yang mengering di bawah matahari Sumenep, tersimpan sejarah, kesabaran, dan doa yang seharusnya tidak layu oleh kelalaian.
Dan mungkin, hanya ketika negara benar-benar hadir di ladang-ladang itu, keharuman tembakau Sumenep akan kembali berarti bukan hanya bagi industri, tetapi bagi manusia yang menanamnya.
***
*) Oleh : Syafiqurrahman, Sekretaris Umum PC PMII Sumenep.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |