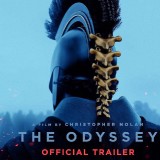TIMES SUMENEP, SUMENEP – Belakangan ini dunia akademik Indonesia sedang dilanda fenomena yang oleh sebagian kalangan disebut “tsunami jurnal”. Bukan soal gempa dan air bah, tapi tentang gelombang besar keharusan menerbitkan jurnal ilmiah, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun institusi pendidikan tinggi. Ironisnya, fenomena ini lebih banyak berorientasi pada syarat administratif ketimbang semangat keilmuan.
Mahasiswa strata satu harus punya publikasi minimal di jurnal kampus untuk syarat wisuda, mahasiswa S2 wajib publikasi minimal sinta 3 atau 4, dan mahasiswa S3 apalagi harus internasional bereputasi.
Belum lagi dosen yang demi kepangkatan akademik dan sertifikasi, wajib punya sekian artikel di jurnal bereputasi tertentu. Seakan-akan akademik hari ini bukan lagi soal gagasan atau inovasi, tapi angka di daftar jurnal.
Tak bisa dipungkiri, ide awalnya sangat mulia. Publikasi ilmiah bertujuan menyebarkan pengetahuan, berbagi temuan baru, sekaligus membuka ruang diskusi antarilmuwan. Namun, di Indonesia, yang terjadi justru pemaksaan administratif. Mahasiswa dipaksa menulis jurnal bukan karena ingin menyumbang ide, tapi semata karena harus lulus.
Coba saja tanya ke mahasiswa akhir, berapa persen yang menulis jurnalnya dengan sungguh-sungguh ingin berkontribusi? Pasti sebagian besar karena syarat. Bahkan banyak yang tak paham betul isinya, asal submit, asal terbit.
Beban ini diperparah dengan budaya kampus yang lebih mengutamakan angka publikasi daripada kualitas substansi. Tidak jarang dosen menganggap mahasiswa yang cepat terbit jurnalnya lebih unggul ketimbang yang mungkin risetnya lebih berbobot tapi belum tayang karena proses panjang di jurnal kredibel.
Fenomena tsunami jurnal ini juga membuka celah bisnis baru. Munculnya jasa submit jurnal, jasa pembuatan artikel ilmiah, hingga broker penerbitan jurnal jadi gejala yang tak terhindarkan. Hanya dengan sejumlah uang, artikel bisa masuk jurnal nasional, bahkan internasional. Ini jelas problem etika akademik.
Lebih gawat lagi, banyak jurnal predator bermunculan. Jurnal-jurnal ini memanfaatkan kegelisahan mahasiswa dan dosen yang dikejar-kejar kewajiban publikasi. Dengan iming-iming terbit cepat dan biaya tertentu, artikel diterbitkan tanpa seleksi ketat, tanpa review yang memadai. Akibatnya, kualitas publikasi akademik Indonesia jadi dipertanyakan di mata dunia.
Bayangkan, di satu sisi kita ingin mendongkrak kualitas riset nasional, di sisi lain justru memfasilitasi maraknya jurnal abal-abal. Akhirnya, publikasi hanya jadi formalitas tanpa makna akademik.
Efek dari tsunami jurnal ini bukan cuma soal kualitas akademik yang menurun, tapi juga memicu kecemasan kolektif di lingkungan kampus. Mahasiswa diburu-buru menerbitkan jurnal, padahal minim pembekalan tentang cara menulis artikel ilmiah yang benar. Dosen pun tertekan dengan tuntutan kuota publikasi demi jabatan akademik.
Tak jarang, kreativitas akademik jadi korban. Karena lebih sibuk memenuhi target kuantitas daripada memikirkan gagasan berkualitas. Banyak dosen dan mahasiswa asal menulis topik yang ringan dan aman demi cepat terbit. Topik-topik kritis yang seharusnya diperdebatkan di ruang akademik jadi minim. Kampus pelan-pelan berubah jadi pabrik jurnal.
Sejatinya, publikasi ilmiah haruslah menjadi ruang gagasan, laboratorium pemikiran, sekaligus tempat mempertemukan perbedaan pandangan secara ilmiah. Bukan sekadar alat administratif.
Kita butuh keberanian untuk mulai menggeser paradigma ini. Publikasi bukan soal angka terbit, tapi tentang kontribusi terhadap bidang ilmu dan masyarakat. Harus ada keberanian kampus untuk tidak menjadikan jumlah publikasi sebagai satu-satunya indikator mutu akademik.
Lebih baik sedikit jurnal, tapi benar-benar hasil riset serius, ketimbang tumpukan jurnal basa-basi tanpa substansi. Kampus juga perlu aktif melatih mahasiswa dan dosennya tentang cara menulis artikel ilmiah yang baik, bukan hanya mengajari cara submit.
Di sisi lain, pemerintah dan lembaga akreditasi juga harus berbenah. Jika terus menerapkan kebijakan berbasis kuantitas publikasi tanpa mempertimbangkan kualitas dan relevansi, maka budaya akademik kita akan terus terjebak di lingkaran tsunami jurnal ini.
Kebijakan seperti publikasi internasional bereputasi sebagai syarat wisuda patut dievaluasi. Bukan dihapuskan, tapi diberi ruang fleksibilitas sesuai konteks dan kapasitas kampus masing-masing. Kampus di daerah tentu tak bisa disamakan dengan perguruan tinggi besar di ibu kota atau di luar negeri.
Jika dibiarkan, fenomena tsunami jurnal ini hanya akan menghasilkan generasi akademik yang haus gelar dan angka publikasi, tapi minim gagasan dan pengaruh nyata di masyarakat. Kampus jadi pabrik skripsi, pabrik tesis, dan pabrik artikel bukan lagi rumah gagasan.
***
*) Oleh: Syafiqurrahman, Sekretaris Umum PC PMII Sumenep.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |